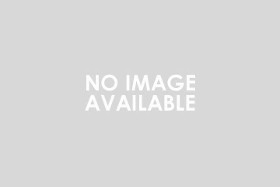
Pengertian Kepahlawanan yang Berkembang
Setiap bangsa memerlukan pahlawan. Mereka bukan sekadar nama dalam buku sejarah, melainkan simbol tentang apa yang dianggap penting oleh bangsa itu sendiri: keberanian, integritas, dan kemampuan menegakkan kebenaran di tengah tekanan kekuasaan. Namun makna kepahlawanan tidak pernah statis. Ia selalu berubah mengikuti tantangan zamannya. Dalam arti yang paling luas, seorang pahlawan adalah mereka yang memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan bangsa—baik dalam membangun kemerdekaan, menegakkan hukum, memperkuat lembaga, maupun melindungi kebebasan berpikir.
Dengan pengertian itu, sosok Ali Sadikin menempati tempat istimewa dalam sejarah kita. Ia bukan hanya gubernur yang membangun Jakarta, tetapi seorang negarawan yang menanamkan nilai paling penting bagi demokrasi: bahwa kekuasaan harus dikoreksi.
Relativitas Kepahlawanan
Daftar pahlawan nasional kita panjang, tetapi tidak selalu objektif. Banyak tokoh dengan jasa luar biasa belum diakui secara formal, sementara ada yang diangkat karena pertimbangan politik. Sebutlah Prof. Widjojo Nitisastro, arsitek utama pembangunan ekonomi Indonesia pasca-1960-an. Ia membawa Indonesia dari negara berpendapatan hanya US$180 per kapita dengan 85% penduduk buta huruf menjadi negara berpendapatan menengah dengan capaian luar biasa dalam Indeks Pembangunan Manusia. Namun jasanya belum diabadikan sebagai pahlawan nasional.
Fakta ini mengingatkan kita bahwa kepahlawanan tidak selalu lahir dari perang atau berseragam militer. Ada pahlawan yang berjuang di ruang kebijakan, di ruang pengadilan, dan—seperti Ali Sadikin—di ruang publik, menegakkan kebebasan berpikir.
Ali Sadikin dan Keberanian Institusional
Bagi banyak orang, Ali Sadikin dikenal karena membangun Jakarta secara fisik: taman kota, infrastruktur, dan ruang publik. Tetapi kontribusi sejatinya jauh lebih dalam: ia membangun institusi yang melahirkan kebebasan sipil. Saat memimpin Jakarta (1966-1977), Bang Ali mendirikan Majalah Tempo, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Taman Ismail Marzuki (TIM). Ketiganya menjadi simbol demokrasi Indonesia yang hidup—ruang di mana warga negara dapat berpikir, berbicara, dan berkarya tanpa takut pada kekuasaan.
Langkah itu bukan kebetulan. Ali Sadikin percaya bahwa kemajuan bangsa hanya mungkin jika kebebasan dijamin. Ia tahu, kekuasaan yang tak dikoreksi akan kehilangan arah moralnya. Dalam suasana politik yang masih otoriter kala itu, keputusan seorang gubernur untuk melahirkan media dan lembaga yang berpotensi mengkritik pemerintah pusat merupakan tindakan yang luar biasa berani.
Kebebasan Pers di Tengah Tekanan
Kini, lebih dari lima dekade kemudian, nilai yang diperjuangkan Ali Sadikin itu kembali diuji. Tempo—majalah yang lahir dari keberaniannya—kembali diserang karena keberaniannya bersuara. Gugatan hukum sebesar Rp200 miliar yang diajukan Menteri Pertanian terhadap Tempo mengingatkan kita pada praktik SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)—gugatan besar untuk membungkam kritik. Cara seperti ini pernah dipakai Donald Trump terhadap media di Amerika Serikat: bukan untuk mencari kebenaran hukum, tetapi untuk menebar ketakutan.
Jika pola seperti ini dibiarkan, Indonesia akan mundur jauh ke belakang. Pers akan berhitung sebelum menulis, dan publik akan kehilangan sumber koreksi terhadap kekuasaan. Padahal, sebagaimana diajarkan Ali Sadikin, negara yang sehat justru membutuhkan pers yang berani.
Pers, Kebenaran, dan Fungsi Koreksi
Ali Sadikin tidak pernah menganggap pers sebagai musuh. Ia memahami bahwa media adalah mitra moral kekuasaan. Ia pernah berucap bahwa pemimpin membutuhkan lawan yang sepadan agar keputusan yang diambil tetap benar. Tempo, bagi dia, adalah bagian dari mekanisme itu: media yang berani, namun juga bertanggung jawab.
Pers yang bebas memungkinkan pemerintah melihat apa yang berjalan baik dan apa yang tidak. Tanpa informasi jujur dari lapangan, kekuasaan akan terjebak dalam kebohongan yang diciptakannya sendiri. Ali Sadikin sering mengingatkan: pandemi sosial bukan berasal dari virus, melainkan dari keheningan (silence), pengabaian (ignorance), dan ketakutan (fear). Ketika masyarakat takut berbicara, ketika kebenaran dikubur atas nama stabilitas, di situlah kemunduran dimulai.
Amartya Sen pernah menulis, “Tidak ada kelaparan massal di negara yang menjamin kebebasan pers.” Kalimat itu relevan bagi Indonesia. Kebebasan informasi bukan ancaman bagi stabilitas, melainkan syarat bagi keberlanjutan bangsa.
Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan yang Lemah
Selain Tempo, warisan penting lain dari Ali Sadikin adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ia bukan hanya memberi izin berdirinya LBH, tetapi memastikan lembaga itu hidup—dengan dukungan finansial dan sumber daya manusia yang memadai. LBH menjadi ruang bagi masyarakat kecil mencari keadilan ketika pasar politik dan hukum tidak berpihak pada mereka.
Langkah ini menunjukkan kualitas kepemimpinan yang langka: keberanian melahirkan lembaga yang bisa mengoreksi dirinya sendiri. Ali Sadikin tahu, kekuasaan yang tak diimbangi kritik akan tergelincir pada kesewenang-wenangan.
Pemimpin Alpha dan Keberanian Moral
Ali Sadikin adalah contoh pemimpin alpha yang kuat sekaligus reflektif—mirip atlet besar seperti Michael Jordan, LeBron James, atau Kobe Bryant yang berani menantang dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, tetapi pada kemampuan untuk dikoreksi.
Kepemimpinannya mengajarkan bahwa menjaga kepentingan publik berarti menundukkan self-interest. Dalam politik modern yang sering terjebak pada ego pribadi dan kalkulasi kekuasaan, pesan ini terasa semakin relevan. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan berarti menuntut kepatuhan, melainkan menciptakan ruang di mana kritik dapat lahir tanpa rasa takut.
Makna Kepahlawanan Hari Ini
Apa makna kepahlawanan di masa kini? Bukan lagi perang di medan senjata, melainkan perjuangan mempertahankan ruang kebebasan dan kebenaran. Di tengah ancaman gugatan hukum terhadap media, pembatasan kebebasan berpikir, dan melemahnya independensi lembaga, nilai-nilai yang pernah ditegakkan Ali Sadikin menjadi mercusuar moral bagi kita semua.
Jika hari ini Tempo diserang karena keberaniannya menulis, maka yang sedang diuji bukan hanya satu media, melainkan daya tahan demokrasi Indonesia itu sendiri. Pers yang berani adalah bagian dari sistem check and balance yang dulu dibangun Ali Sadikin—sistem yang membedakan negara demokratis dari negara otoriter.
Warisan Ali Sadikin
Warisan terbesar Ali Sadikin bukan hanya kota Jakarta yang lebih tertata, tetapi budaya politik yang menghormati kritik dan hukum. Ia menanamkan keyakinan bahwa membangun bangsa tidak cukup dengan gedung tinggi dan jalan lebar; yang lebih penting adalah membangun institusi yang membuat kebenaran bisa hidup.
Kini, ketika sebagian elite berusaha membungkam kritik melalui jalur hukum atau kekuasaan, warisan itu terasa semakin berharga. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin dengan keberanian moral seperti Ali Sadikin—pemimpin yang mengerti bahwa kekuasaan sejati adalah kekuasaan yang mau diawasi.
Penutup: Ali Sadikin dan Kita
Ali Sadikin mungkin tidak sempurna; tidak ada pahlawan yang sempurna. Tetapi ia memberi teladan bahwa pemimpin sejati tidak takut pada kritik—bahkan melindungi mereka yang mengkritiknya. Hari ini, ketika Tempo menghadapi tekanan hukum besar, kita seharusnya mengingat kembali semangat pendirinya: bahwa kebebasan pers bukan milik wartawan semata, melainkan milik seluruh bangsa. Tanpa pers yang bebas, tidak ada ruang bagi kebenaran; dan tanpa kebenaran, tidak ada bangsa yang bisa disebut beradab.
Jika Ali Sadikin masih bersama kita, saya yakin ia akan berdiri di sisi Tempo—bukan karena kesetiaan personal, tetapi karena keyakinan bahwa kebebasan adalah fondasi paling mulia dari kepahlawanan.
Berkomentarlah dengan bijak, bagi yang memberikan link aktif akan langsung hapus. Terima Kasih